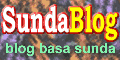Sundanet• 14 Des 2004 • Kategori: Seni dan Budaya
Sebagai orang yang tidak pernah berinteraksi secara mendalam dengan Kang Ajip Rosidi (KAR), maka ketika diminta untuk memberi pandangan terhadap KAR, satu-satunya upaya yang bisa dilakukan adalah membaca buku-bukunya. Karena tinjauannya lebih kepada pemahaman terhadap sosok pribadi (bukan telaah karya sastra), maka pilihan jatuh kepada buku-buku karya KAR yang menurut KAR sendiri “jiga otobiografi atawa memoar” atau “panineungan”. Adapun buku-buku yang dianggap “jiga otobiografi atawa memoar” dan “panineungan” tersebut adalah : Hurip Waras (1988), Beber Layar (Cetakan ke 1 tahun 1964), Pancakaki (1993), Trang-trang Kolentrang (1999), Ucang-Ucang Angge (2000).
Setelah membaca buku-buku tersebut, kesimpulannya, KAR adalah sosok “orang Sunda moderen”. Sengaja kalimat “orang Sunda Moderen” disatukan di dalam satu tanda petik, karena apabila bicara orang Sunda yang ada dewasa ini bisa jadi banyak yang belum “moderen”, sementara kata moderen sendiri apabila tidak dikaitkan dengan kata-kata orang Sunda, akan mempunyai arti yang sangat luas yang pada tingkat tertentu dapat menghilangkan identitas “kasundaan”.
Ada beberapa kriteria yang digunakan untuk merujuk istilah “moderen” dalam kaitannya dengan orang Sunda disini. Pertama, adalah perhatian, “kanyaah” dan bahkan “prak”nya “ngamumule” kebudayaan Sunda. Sebagai orang Sunda “pituin”, tanggung jawab dan “kanyaah” KAR kepada budaya Sunda tidak dapat diragukan lagi. Walaupun KAR mulai berkiprah di dunia sastra Sunda setelah terlebih dahulu menggeluti sastra Indonesia, namun pada perkembangan berikutnya perhatian, kerja nyata dan yang lebih penting lagi kontinyuitas untuk “ngamumule” budaya Sunda khususnya sastra Sunda berlangsung terus sampai hari ini.
Selain menulis karya sastra Sunda nya sendiri, tulisan-tulisan KAR mengenai sastra Sunda, baik berupa pemikiran, kritik, ulasan mengalir terus sampai saat ini. Buku Beber Layar, sebagai kumpulan karangan yang ditulis oleh KAR pada saat berusia antara 18 sampai 22 tahun, substansinya masih tetap “up to date”.
Walaupun bermukim di Jepang, KAR masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan nyata untuk Ki Sunda dalam bentuk pemberian hadiah sastra Rancage, Kongres Internasional Budaya Sunda, membuat penerbitan berbahasa Sunda (yang paling monumental: membuat ensiklopedi Sunda) dan kegiatan “kasundaan” lainnya. Suatu aktifitas yang langka dilakukan baik, oleh orang-orang dari suku lain tentang budayanya dan oleh orang-orang Sunda sendiri yang ada di kampung halamannya. Untuk hadiah sastra Rancage, selain sudah teruji kontinyuitasnya sejak tahun 1989 (di Indonesia konon tidak pernah ada pemberian hadiah sastra yang berlangsung secara berkesinambungan seperti Rancage), juga yang tidak kalah pentingnya, hadiah sastra Rancage tersebut bukan hanya untuk sastra Sunda tetapi juga untuk sastra Jawa dan Bali.
Pemberian perhatian yang bukan hanya untuk sastra Sunda ini menunjukkan bahwa KAR tidak termasuk kepada orang yang “etnocentris”, provinsialis atau sukuisme dalam arti sempit. Karena itu, kriteria ke dua untuk menunjuk kemoderenan KAR adalah ke- Indonesiaan. Kiprah KAR di dalam dunia sastra Indonesia sudah dimulai sejak SMP. Karena kiprahnya dalam kesusasteraan Indonesia itulah, pada usia yang sangat belia (16 tahun) sudah bisa mengikuti Kongres Kebudayaan di Solo, dengan ongkos yang diberikan secara khusus oleh Mr. Muhammad Yamin yang kala itu menjadi Menteri PP dan K (Hurip Waras, hal 50). Selain daripada itu, pada usia yang cukup muda pula (19 tahun) KAR mendapat Hadiah Sastra Nasional pada Kongres Kebudayaan tahun 1957 di Denpasar. Kiprah di tingkat nasional ini berlanjut diantaranya menjadi redaksi PN Balai Pustaka (1955-1956), Ketua Dewan Kesenian Jakarta, Ketua IKAPI, Staf Ahli Menteri P&K dsb. Selain dari pada itu karya-karya KAR juga sudah diterjemahkan dan diterbitkan ke dalam bahasa Inggris, Perancis, Belanda, Hindi, Jepang, Rusia dan Cina.
Rasa cintanya terhadap tanah air, diantaranya diwujudkan dalam bentuk tulisan yang dikumpulkannya di dalam buku “Trang trang Kolentrang” : Politik Reformasi Dina Surat - surat ti Jepang. Disini kita pun melihat bahwa perhatian KAR terhadap dunia politik sangat besar.
Kriteria kemoderenan KAR yang ke tiga, adalah “go international”. Pengertian “go international” disini tidak hanya diukur oleh kehadiran fisik, tetapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah pemahaman pemikiran yang berkembang di dunia internasional. Sebagai budayawan “moyan”, KAR sudah sejak muda bergelut dengan pemikiran-pemikiran para pemikir Barat baik melalui bacaan maupun melalui diskusi dengan para sastrawan/pemikir saat itu. Kedudukannya sebagai profesor tamu di Osaka Jepang sejak tahun 1981 lebih memantapkan dirinya sebagai manusia “internasional”.
Kalaulah inti dari tulisan ini mengemukakan bahwa KAR adalah sosok manusia Sunda moderen, dengan dua kriteria terakhir pengertiannya adalah, walaupun KAR sudah berkecimpung di dunia nasional dan internasional, namun ciri-ciri bahkan kiprahnya di dalam “kasundaan” tidaklah surut. KAR bukan saja bisa “pindah cai - pindah tampian”, tetapi lebih jauh dari itu kiprahnya di dunia nasional dan internasional justru bisa lebih memberikan kontrbusi yang lebih positif terhadap “kasundaan”. Padahal banyak orang yang menyebutkan bahwa pada umumnya para “gegeden” Sunda itu “hapa” budaya. Jangankan jauh-jauh yang tinggal/hidup di Jakarta atau di luar negeri, mereka yang hidup dan tinggal di Bandung saja perhatiannya terhadap budaya Sunda ini sangat kurang.
Keempat, karena antara Islam - Sunda dengan Sunda - Islam, sering disatu nafaskan, maka di dalam konteks modernitas manusia Sunda, unsur-unsur ke Islaman tidak boleh ditinggalkan. Artinya semoderen apapun orang Sunda, apabila masih ingin disebut orang Sunda, maka di luar tanggung jawabnya terhadap “kasundaan”, ciri dan prilaku ke-Islamannyapun harus tetap nampak. Walaupun pada awalnya (ketika kelas II SMP) KAR senang “fifilsfatan” tentang eksistensi Tuhan, tapi prilaku ke-Islaman KAR juga “kelihatannya” cukup “leket?”. Sebagaimana kebanyakan orang Sunda, walaupun KAR sudah beragama Islam sejak lahir, namun pemahaman tentang Islam dimulai lagi melalui proses pencarian, terutama setelah membaca karya-karya HHM. Kedekatannya dengan beberapa tokoh Pelajar Islam Indonesia (PII) Jawa Barat (ketika sekretariatnya masih di Gg.Asmi) seperti Mang Endang Sjaefudin Anshari atau Kang Josef (yang kemudian jadi besannya), sedikit banyak menambah pemahaman tentang Islam itu sendiri.
Sikap KAR tentang keterkaitan antara Sunda dengan Islam diantaranya :
“sadar kana kaetnisan budayana nu Sunda sabada leuwih ti heula ngarasa jadi muslim, justru kudu mageuhan adeg-adegna nu nyumber kana ajen-inajen ka Islaman, tapi oge baris ngabeungharan warna budaya umat. Neuleuman jeung neangan ajen-inajen ka Sundaan tanwande baris nambahan kakayaan budaya umat”.
Untuk urusan ke - Islaman ini, salah satu “peristiwa budaya” penting ketika KAR menjadi ketua DKJ adalah pembangunan mesjid Amir Hamzah di Taman Ismail Marzuki.
Kelima, unsur kerja keras. Prof. Herman Soewardi di dalam berbagai kesempatan seringkali mengemukakan bahwa salah satu ciri bangsa Indonesia (termasuk suku Sunda) adalah lemah karsa, dalam pengertian bahwa kalaupun bekerja seringkali tidak “junun”. Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa untuk kasus KAR, aspek kinerja yang “memble” ini ditemukan. KAR bisa disebut sebagai pekerja keras dan mempunyai semangat kerja yang tinggi. Ketika di SMA saja, walaupun KAR masuk ke sekolah B, namun karena keingin tahuan yang besar mengenai keseustraan yang mengebu-gebu, siang harinya KAR sekolah di SMA Perjoangan. Sampai saat ini bisa jadi belum ada orang Sunda yang karyanya sebanyak yang dibuat oleh KAR. Kalaulah salah satu ciri dari sosok manusia moderen itu profesianal, dalam pengertian ahli dan kompeten maka KAR sudah termasuk post_category ini.
Untuk karya-karyanya dalam bentuk memoar, perlu mendapat apresiasi secara khusus. Karya-karya tersebut mengandung banyak hal yang dapat dikatagorikan sebagai sejarah kontemporer. Dalam hal ini KAR menjadi saksi hidup dari suatu proses yang terjadi di dalam sejarah. Selama ini pelajaran sejarah seringkali hanya menunjukkan kejadian-kejadian yang kadangkala kering dari aspek “human interest”. Memoar KAR bisa menjadi pelengkap tentang apa-apa yang terjadi di balik panggung sejarah.
Karena bentuknya memoar, maka pada tataran tertentu perlu dilakukan pendalaman. Tugas itu tentu saja tidak bisa dibebankan kepada KAR. Dalam konteks memoar, KAR dapat disebut sebagai pembuka jalan. Sebagai contoh, di luar apa yang ditulis KAR tentang Kongres Pemuda Sunda dan “setting” sosialnya sehingga kongres tersebut dilaksanakan, sampai saat ini belum ada lagi buku yang membeberkan secara tuntas, gamblang dan ilmiah tentang hal itu (terutama tentang Pergerakan Sunda pada akhir tahun lima puluhan). Akibat dari “kekosongan” sejarah ini, hampir selama periode Orde Baru (bahkan mungkin sampai sekarang), banyak orang Sunda yang merasa menanggung dosa warisan, dari suatu perjalanan sejarah Ki Sunda yang tidak jelas kejadiannya.
Karena kejelian dan kerajinannya mengumpulkan bahan-bahan, KAR bisa disebut sebagai “arsip hidup” Ki Sunda terlengkap saat ini. Di luar hal-hal yang sudah diungkapkannya saat ini (dalam bentuk buku), bisa jadi masih banyak hal lain yang perlu kita korek. Sebagai contoh, walaupun di dalam buku “Ucang-ucang Angge”, KAR menceriterakan ketokohan Prof. Dr. Doddy A. Tisnaamidjaja, namun isinya berbicara pula tentang hiruk pikuk pemilihan Gubernur Jawa Barat pada tahun 1967 (kejadiannya hampir mirip dengan pemilihan Gubernur Jawa Barat saat ini). Ketika membicarakan Ilen Surianegara, walaupun sepintas kita diajak untuk mengetahui polemik di sekitar naskah Wangsakerta. Demikian pula halnya dengan tulisan yang diberi judul RHM. Akil Prawiradiredja ( berkaitan dengan pemilihan Wagub), atau tentang Dajat Hardjakusumah yang selain berbicara tentang dunia kewartawanan saat itu, juga berbicara tentang situasi di sekitar kejadian G30S/PKI.
Melihat kejelian dan kerajinan membuat memoar yang notabene sejarah ini dengan sangat tepat di dalam jilid luar bagian belakang dari buku Ucang-ucang Angge diungkapkan:
“Lain wae kudu dideudeul data anu akurat, tapi deuih kudu panjang ingetan. Heueuh, mun urang aya karep nulis memoar, boh ngeunaan peristiwa boh ngeunaan kahirupan sajumlahing tokoh; kawas anu dipidangkeun dina ieu buku. Hamo bisa mun ukur ngandelkeun data meunang ngalelebah mah, komo mun bari geus loba poho”
“Naon-naon wae anu dipidangkeun dina ieu buku, lain wae ukur ngasongkeun rupa-rupa informasi ngeunaan sajumlahing tokoh katut patalina sareng rupa-rupa peristiwa, tapi deuih bisa dijadikeun eunteung tuladaneun”
Upaya mengemukakan keadaan juga dilakukannya dengan cara menulis surat kepada sahabat-sahabatnya. Walaupun dalam bentuk surat yang pendek, namun dengan surat itu KAR bisa mengungkapkan situasi dan juga pemikiran-pemikiran KAR tentang berbagai hal.
Ke enam, jaringan pertemanan. Teori-teori manajemen moderen menyebutkan bahwa unsur jaringan (net working) adalah merupakan salah satu faktor penting di dalam mencapai keberhasilan. Apabila membaca memoar KAR, dapat diketahui bahwa kenalan KAR sangat banyak dan dari berbagai kalangan. Sudah sejak kecil, KAR bergaul dengan para tokoh di bidang sastra, pemerintahan, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh politik dsb. Inti pertemanan selain silaturahmi juga untuk menambah wawasan tentang sesuatu. Dari memoar yang dibuat oleh KAR, pertemanan KAR dengan orang-orang yang ditulisnya di dalam memoar tersebut, ternyata tidak hanya sebatas kenal (wawuh munding), tetapi lebih dari itu.
Walaupun teman-temannya cukup banyak dan sangat akrab, tetapi di dalam hal-hal yang dianggap prinsip, KAR bisa sangat kritis. Oleh karena itu perjalanan hidup KAR seringkali ditandai dengan percikan-percikan konflik yang kadangkala sangat terbuka. Untuk ukuran budaya Sunda - bahkan mungkin untuk budaya Barat sekalipun, kritik-kritik yang dilakukan oleh KAR seringkali dirasakan sangat tajam. Sebagai contoh, kritikannya terhadap Pak Ilen Surianegara, Pak Mashudi atau kepada Prof. Achmad Sanusi. Pada awalnya sikap KAR seperti itu, diperkirakan terpengaruh (seperti agama) oleh teman-temannya di PII yang juga seringkali prinsipalis. Namun, setelah membaca otobiografi dan memoarnya, ternyata sikap kritis tersebut sudah ada sejak masa kecilnya. Sebagai contoh, ketika SMP, KAR pernah diusir oleh guru bahasa Indonesia, karena dianggap sok pintar. Pada perkembangan berikutnya, kitapun bisa melihat “dedegler” nya KAR di dalam mensikapi berbagai masalah sastra Sunda setelah perang (baca: Beber Layar) atau kritik terhadap LBSS di media masa pada tahun sembilan puluhan.
Kalaulah dianggap sebagai “kekurangan” maka hal tersebut bisa dianggap sebagai kekurangan KAR. Atau kalau berfikirnya positif, yang salah itu bukanlah KAR, tetapi orang Sunda pada umumnya, yang belum siap berbeda pendapat secara terbuka.
Terlepas apakah itu kekurangan atau bukan, hal penting yang perlu ditelusuri, bagaimana Ki Sunda bisa melahirkan salah satu rundayannya menjadi KAR?. Apabila membaca Hurip Waras, inti dari keberhasilan KAR dimulai dari “resep maca”. Karena salah satu strategi penting yang harus dibangun ke depan adalah membuka ruang dan memperbanyak buku bacaan agar sejak dini, anak-anak menyenangi bacaan - termasuk bacaan berbahasa Sunda.Memang ketika ruang itu dibuka, jangan harap semua orang bisa memanfaatkannya, karena dari Jatiwangi juga hanya lahir seorang KAR. Tetapi pengalaman-pengalaman negara maju menunjukkan bahwa dengan dibukanya “ruang” bagi masyarakat untuk rajin membaca, peluang melahirkan orang-orang seperti KAR menjadi semakin besar. Ternyata dengan rajin membaca, orang tidak kalah pinternya dengan yang memiliki ijasah sekalipun (apalagi kalau ijasahnya bukan dari hasil belajar yang sungguh-sungguh).
Kedua, kebiasaan KAR ketika kecil untuk nonton kesenian (wayang kulit), membawa bekas sehingga melahirkan benih-benih rasa bertanggung jawab terhadap eksistensi kesenian. Selain daripada itu, karena sejak kecil sudah hafal kepada konvensi ceritera wayang, sedikit banyak ceritera-ceritera itu telah pula membantu membangun runtuyan logika berfikir dan mengembangkan imajinasi.
Ketiga, apakah lahirnya KAR seperti sekarang ini sesuai juga dengan sinyalemen KAR: bahwa agar orang Sunda maju, harus keluar (berada) dari luar tatar Sunda? (sehingga KAR pun akan menghabiskan masa tuanya di luar tatar Sunda?).
Dengan menulis catatan singkat ini, ada suatu perjalanan pemikiran yang berujung pada pemahaman: “bahwa untuk menjadi moderen, manusia tidak perlu kehilangan ciri-ciri etnisitas dan keagamaannya” atau bisa disebutkan bahwa: “aspek etnisitas dan keagamaan termasuk merupakan ciri pelengkap yang tidak dapat dipisahkan dari kemoderenian seseorang” (selama ini secara sosiologis antara modern dan tradisi termasuk agama sering dibuat dikhotomi).
Berbahagialah orang Sunda, karena telah memiliki tokoh sekaliber Ajip Rosidi. Hatur nuhun Kang Ajip. Panjang umur, istiqomah, khusnul khotimah dan terus berkarya. Untuk ke depan diharapkan ada yang dapat menulis tentang KAR secara lebih lengkap, mendalam dan kritis.
Cigadung, 27 Mei 2003
Senin, 09 Maret 2009
Sabtu, 07 Maret 2009
Kerajaan Sunda
 Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebasWilayah bekas Kerajaan Sunda
Kerajaan Sunda (669-1579 M), menurut naskah Wangsakerta merupakan kerajaan yang berdiri menggantikan kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Sunda didirikan oleh Tarusbawa pada tahun 591 Caka Sunda (669 M). Menurut sumber sejarah primer yang berasal dari abad ke-16, kerajaan ini merupakan suatu kerajaan yang meliputi wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Banten, Jakarta, Provinsi Jawa Barat , dan bagian barat Provinsi Jawa Tengah.
Berdasarkan naskah kuno primer Bujangga Manik (yang menceriterakan perjalanan Bujangga Manik, seorang pendeta Hindu Sunda yang mengunjungi tempat-tempat suci agama Hindu di Pulau Jawa dan Bali pada awal abad ke-16), yang saat ini disimpan pada Perpustakaan Boedlian, Oxford University, Inggris sejak tahun 1627), batas Kerajaan Sunda di sebelah timur adalah Ci Pamali ("Sungai Pamali", sekarang disebut sebagai Kali Brebes) dan Ci Serayu (yang saat ini disebut Kali Serayu) di Provinsi Jawa Tengah.
Tome Pires (1513) dalam catatan perjalanannya, Suma Oriental (1513 – 1515), menyebutkan batas wilayah Kerajaan Sunda di sebelah timur sebagai berikut:
“
Sementara orang menegaskan bahwa kerajaan Sunda meliputi setengah pulau Jawa. Sebagian orang lainnya berkata bahwa Kerajaan Sunda mencakup sepertiga Pulau Jawa ditambah seperdelapannya lagi. Katanya, keliling Pulau Sunda tiga ratus legoa. Ujungnya adalah Ci Manuk.
”
Menurut Naskah Wangsakerta, wilayah Kerajaan Sunda mencakup juga daerah yang saat ini menjadi Provinsi Lampung melalui pernikahan antara keluarga Kerajaan Sunda dan Lampung. Lampung dipisahkan dari bagian lain kerajaan Sunda oleh Selat Sunda.
[1] Hubungan Kerajaan Sunda dengan Eropa
Kerajaan Sunda sudah lama menjalin hubungan dagang dengan bangsa Eropa saperti Inggris, Perancis dan Portugis. Kerajaan Sunda malah pernah menjalin hubungan politik dengan bangsa Portugis. Dalam tahun 1522, Kerajaan Sunda menandatangani Perjanjian Sunda-Portugis yang membolehkan orang Portugis membangun benteng dan gudang di pelabuhan Sunda Kelapa. Sebagai imbalannya, Portugis diharuskan memberi bantuan militer kepada Kerajaan Sunda dalam menghadapi serangan dari Demak dan Cirebon (yang memisahkan diri dari Kerajaan Sunda).
[2] Sejarah
Sebelum berdiri sebagai kerajaan yang mandiri, Sunda merupakan bawahan Tarumanagara. Raja Tarumanagara yang terakhir, Sri Maharaja Linggawarman Atmahariwangsa Panunggalan Tirthabumi (memerintah hanya selama tiga tahun, 666-669 M), menikah dengan Déwi Ganggasari dari Indraprahasta. Dari Ganggasari, beliau memiliki dua anak, yang keduanya perempuan. Déwi Manasih, putri sulungnya, menikah dengan Tarusbawa dari Sunda, sedangkan yang kedua, Sobakancana, menikah dengan Dapuntahyang Sri Janayasa, yang selanjutnya mendirikan kerajaan Sriwijaya. Setelah Linggawarman meninggal, kekuasaan Tarumanagara turun kepada menantunya, Tarusbawa. Hal ini menyebabkan penguasa Galuh, Wretikandayun (612-702) memberontak, melepaskan diri dari Tarumanagara, serta mendirikan Galuh yang mandiri. dari pihak Tarumanagara sendiri, Tarusbawa juga menginginkan melanjutkan kerajaan Tarumanagara. Tarusbawa selanjutnya memindahkan kekuasaannya ke Sunda, sedangkan Tarumanagara diubah menjadi bawahannya. Beliau dinobatkan sebagai raja Sunda pada hari Radite Pon, 9 Suklapaksa, bulan Yista, tahun 519 Saka (kira-kira 18 Mei 669 M). Sunda dan Galuh ini berbatasan, dengan batas kerajaanya yaitu sungai Citarum (Sunda di sebelah barat, Galuh di sebelah timur).
[3] Kerajaan kembar
Putera Tarusbawa yang terbesar, Rarkyan Sundasambawa, wafat saat masih muda, meninggalkan seorang anak perempuan, Nay Sekarkancana. Cucu Tarusbawa ini lantas dinikahi oleh Rahyang Sanjaya dari Galuh, sampai mempunyai seorang putera, Rahyang Tamperan. Saat Tarusbawa meninggal (tahun 723), kekuasaan Sunda jatuh ke Sanjaya, yang di tahun itu juga berhasil merebut kekuasaan Galuh dari Rahyang Purbasora (yang merebut kekuasaan Galuh dari ayahnya, Bratasenawa/Rahyang Séna). Oleh karena itu, di tangan Sanjaya, Sunda dan Galuh bersatu kembali. Untuk meneruskan kekuasaan ayahnya yang menikah dengan puteri raja Keling (Kalingga), tahun 732 Sanjaya menyerahkan kekuasaan Sunda-Galuh ke puteranya, Tamperan. Di Keling, Sanjaya memegang kekuasaan selama 22 tahun (732-754), yang kemudian diganti oleh puteranya dari Déwi Sudiwara, Rarkyan Panangkaran.
Rahyang Tamperan berkuasa di Sunda-Galuh selama tujuh tahun (732-739), lalu membagi kekuasaan pada dua puteranya: Sang Manarah (dalam carita rakyat disebut Ciung Wanara) di Galuh serta Sang Banga (Hariang Banga) di Sunda. Sang Banga (Prabhu Kertabhuwana Yasawiguna Hajimulya) menjadi raja selama 27 tahun (739-766), tapi hanya menguasai Sunda dari tahun 759.
Dari Déwi Kancanasari, keturunan Demunawan dari Saunggalah, Sang Banga mempunyai putera, bernama Rarkyan Medang, yang kemudian meneruskan kekuasaanya di Sunda selama 17 tahun (766-783) dengan gelar Prabhu Hulukujang. Karena anaknya perempuan, Rakryan Medang mewariskan kekuasaanya kepada menantunya, Rakryan Hujungkulon atau Prabhu Gilingwesi (dari Galuh, putera Sang Mansiri), yang menguasai Sunda selama 12 tahun (783-795). Karena Rakryan Hujungkulon inipun hanya mempunyai anak perempuan, maka kekuasaan Sunda lantas jatuh ke menantunya, Rakryan Diwus (dengan gelar Prabu Pucukbhumi Dharmeswara) yang berkuasa selama 24 tahun (795-819). Dari Rakryan Diwus, kekuasaan Sunda jatuh ke puteranya, Rakryan Wuwus, yang menikah dengan putera dari Sang Welengan (raja Galuh, 806-813). Kekuasaan Galuh juga jatuh kepadanya saat saudara iparnya, Sang Prabhu Linggabhumi (813-842), meninggal dunia. Kekuasaan Sunda-Galuh dipegang oleh Rakryan Wuwus (dengan gelar Prabhu Gajahkulon) sampai ia wafat tahun 891.
Sepeninggal Rakryan Wuwus, kekuasaan Sunda-Galuh jatuh ke adik iparnya dari Galuh, Arya Kadatwan. Hanya saja, karena tidak disukai oleh para pembesar dari Sunda, ia dibunuh tahun 895, sedangkan kekuasaannya diturunkan ke putranya, Rakryan Windusakti. Kekuasaan ini lantas diturunkan pada putera sulungnya, Rakryan Kamuninggading (913). Rakryan Kamuninggading menguasai Sunda-Galuh hanya tiga tahun, sebab kemudian direbut oleh adikna, Rakryan Jayagiri (916). Rakryan Jayagiri berkuasa selama 28 tahun, kemudian diwariskan kepada menantunya, Rakryan Watuagung, tahun 942. Melanjutkan dendam orangtuanya, Rakryan Watuagung direbut kekuasaannya oleh keponakannya (putera Kamuninggading), Sang Limburkancana (954-964). Dari Limburkancana, kekuasaan Sunda-Galuh diwariskan oleh putera sulungnya, Rakryan Sundasambawa (964-973). Karena tidak mempunyai putera dari Sundasambawa, kekuasaan tersebut jatuh ke adik iparnya, Rakryan Jayagiri (973-989).
Rakryan Jayagiri mewariskan kekuasaannya ka puteranya, Rakryan Gendang (989-1012), dilanjutkan oleh cucunya, Prabhu Déwasanghyang (1012-1019). Dari Déwasanghyang, kekuasaan diwariskan kepada puteranya, lalu ke cucunya yang membuat prasasti Cibadak, Sri Jayabhupati (1030-1042). Sri Jayabhupati adalah menantu dari Dharmawangsa Teguh dari Jawa, mertua raja Erlangga (1019-1042).
Dari Sri Jayabhupati, kekuasaan diwariskan kepada putranya, Dharmaraja (1042-1064), lalu ke cucu menantunya, Prabhu Langlangbhumi ((1064-1154). Prabu Langlangbhumi dilanjutkan oleh putranya, Rakryan Jayagiri (1154-1156), lantas oleh cucunya, Prabhu Dharmakusuma (1156-1175). Dari Prabu Dharmakusuma, kekuasaan Sunda-Galuh diwariskan kepada putranya, Prabhu Guru Dharmasiksa, yang memerintah selama 122 tahun (1175-1297). Dharmasiksa memimpin Sunda-Galuh dari Saunggalah selama 12 tahun, tapi kemudian memindahkan pusat pemerintahan kepada Pakuan Pajajaran, kembali lagi ke tempat awal moyangnya (Tarusbawa) memimpin kerajaan Sunda.
Sepeninggal Dharmasiksa, kekuasaan Sunda-Galuh turun ke putranya yang terbesar, Rakryan Saunggalah (Prabhu Ragasuci), yang berkuasa selama enam tahun (1297-1303). Prabhu Ragasuci kemudian diganti oleh putranya, Prabhu Citraganda, yang berkuasa selama delapan tahun(1303-1311), kemudian oleh keturunannya lagi, Prabu Linggadéwata (1311-1333). Karena hanya mempunyai anak perempuan, Linggadéwata menurunkan kekuasaannya ke menantunya, Prabu Ajiguna Linggawisésa (1333-1340), kemudian ke Prabu Ragamulya Luhurprabawa (1340-1350). Dari Prabu Ragamulya, kekuasaan diwariskan ke putranya, Prabu Maharaja Linggabuanawisésa (1350-1357), yang di ujung kekuasaannya gugur di Bubat (baca Perang Bubat). Karena saat kejadian di Bubat, putranya -- Niskalawastukancana -- masih kecil, kekuasaan Sunda sementara dipegang oleh Patih Mangkubumi Sang Prabu Bunisora (1357-1371).
 Prasasti Kawali di Kabuyutan Astana Gedé, Kawali, Ciamis.
Prasasti Kawali di Kabuyutan Astana Gedé, Kawali, Ciamis.Sapeninggal Prabu Bunisora, kekuasaan kembali lagi ke putra Linggabuana, Niskalawastukancana, yang kemudian memimpin selama 104 tahun (1371-1475). Dari isteri pertama, Nay Ratna Sarkati, ia mempunyai putera Sang Haliwungan (Prabu Susuktunggal), yang diberi kekuasaan bawahan di daerah sebelah barat Citarum (daerah asal Sunda). Prabu Susuktunggal yang berkuasa dari Pakuan Pajajaran, membangun pusat pemerintahan ini dengan mendirikan keraton Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati. Pemerintahannya terbilang lama (1382-1482), sebab sudah dimulai saat ayahnya masih berkuasa di daerah timur.
Dari Nay Ratna Mayangsari, istrinya yang kedua, ia mempunyai putera Ningratkancana (Prabu Déwaniskala), yang meneruskan kekuasaan ayahnya di daerah Galuh (1475-1482).
Susuktunggal dan Ningratkancana menyatukan ahli warisnya dengan menikahkan Jayadéwata (putra Ningratkancana) dengan Ambetkasih (putra Susuktunggal). Tahun 1482, kekuasaan Sunda dan Galuh disatukan lagi oleh Jayadéwata (yang bergelar Sri Baduga Maharaja). Sapeninggal Jayadéwata, kekuasaan Sunda-Galuh turun ke putranya, Prabu Surawisésa (1521-1535), kemudian Prabu Déwatabuanawisésa (1535-1543), Prabu Sakti (1543-1551), Prabu Nilakéndra (1551-1567), serta Prabu Ragamulya atau Prabu Suryakancana (1567-1579). Prabu Suryakancana ini merupakan pemimpin kerajaan Sunda-Galuh yang terakhir, sebab setelah beberapa kali diserang oleh pasukan dari Kesultanan Banten, di tahun 1579 kekuasaannya runtuh.
[4] Raja-raja Kerajaan Sunda
Di bawah ini deretan raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Sunda menurut naskah Pangéran Wangsakerta (waktu berkuasa dalam tahun Masehi):
Tarusbawa (menantu Linggawarman, 669 - 723)
Harisdarma, atawa Sanjaya (menantu Tarusbawa, 723 - 732)
Tamperan Barmawijaya (732 - 739)
Rakeyan Banga (739 - 766)
Rakeyan Medang Prabu Hulukujang (766 - 783)
Prabu Gilingwesi (menantu Rakeyan Medang Prabu Hulukujang, 783 - 795)
Pucukbumi Darmeswara (menantu Prabu Gilingwesi, 795 - 819)
Rakeyan Wuwus Prabu Gajah Kulon (819 - 891)
Prabu Darmaraksa (adik ipar Rakeyan Wuwus, 891 - 895)
Windusakti Prabu Déwageng (895 - 913)
Rakeyan Kamuning Gading Prabu Pucukwesi (913 - 916)
Rakeyan Jayagiri (menantu Rakeyan Kamuning Gading, 916 - 942)
Atmayadarma Hariwangsa (942 - 954)
Limbur Kancana (putera Rakeyan Kamuning Gading, 954 - 964)
Munding Ganawirya (964 - 973)
Rakeyan Wulung Gadung (973 - 989)
Brajawisésa (989 - 1012)
Déwa Sanghyang (1012 - 1019)
Sanghyang Ageng (1019 - 1030)
Sri Jayabupati (Detya Maharaja, 1030 - 1042)
Darmaraja (Sang Mokténg Winduraja, 1042 - 1065)
Langlangbumi (Sang Mokténg Kerta, 1065 - 1155)
Rakeyan Jayagiri Prabu Ménakluhur (1155 - 1157)
Darmakusuma (Sang Mokténg Winduraja, 1157 - 1175)
Darmasiksa Prabu Sanghyang Wisnu (1175 - 1297)
Ragasuci (Sang Mokténg Taman, 1297 - 1303)
Citraganda (Sang Mokténg Tanjung, 1303 - 1311)
Prabu Linggadéwata (1311-1333)
Prabu Ajiguna Linggawisésa (1333-1340)
Prabu Ragamulya Luhurprabawa (1340-1350)
Prabu Maharaja Linggabuanawisésa (yang gugur dalam Perang Bubat, 1350-1357)
Prabu Bunisora (1357-1371)
Prabu Niskalawastukancana (1371-1475)
Prabu Susuktunggal (1475-1482)
Jayadéwata (Sri Baduga Maharaja, 1482-1521)
Prabu Surawisésa (1521-1535)
Prabu Déwatabuanawisésa (1535-1543)
Prabu Sakti (1543-1551)
Prabu Nilakéndra (1551-1567)
Prabu Ragamulya atau Prabu Suryakancana (1567-1579)
(5) Rujukan
Aca. 1968. Carita Parahiyangan: naskah titilar karuhun urang Sunda abad ka-16 Maséhi. Yayasan Kabudayaan Nusalarang, Bandung.
Ayatrohaedi. 2005. Sundakala: cuplikan sejarah Sunda berdasarkan naskah-naskah "Panitia Wangsakerta" dari Cirebon. Pustaka Jaya, Jakarta.
Edi S. Ekajati. 2005. Polemik Naskah Pangeran Wangsakerta. Pustaka Jaya, Jakarta. ISBN 979-419-329-1
Yoséph Iskandar. 1997. Sejarah Jawa Barat: yuganing rajakawasa. Geger Sunten, Bandung.
Diperoleh dari "http://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Sunda"
Aca. 1968. Carita Parahiyangan: naskah titilar karuhun urang Sunda abad ka-16 Maséhi. Yayasan Kabudayaan Nusalarang, Bandung.
Ayatrohaedi. 2005. Sundakala: cuplikan sejarah Sunda berdasarkan naskah-naskah "Panitia Wangsakerta" dari Cirebon. Pustaka Jaya, Jakarta.
Edi S. Ekajati. 2005. Polemik Naskah Pangeran Wangsakerta. Pustaka Jaya, Jakarta. ISBN 979-419-329-1
Yoséph Iskandar. 1997. Sejarah Jawa Barat: yuganing rajakawasa. Geger Sunten, Bandung.
Diperoleh dari "http://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Sunda"
Langganan:
Postingan (Atom)